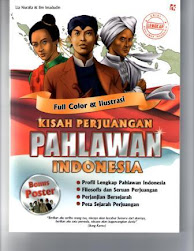Oleh: Iim Imadudin
Kesadaran etnisitas bergerak secara dinami tumbuh dari adanya krisis identitas dan eksistensi. Krisis tersebut muncul akibat gerak sejarah menyangkut eksistensi etnis tersebut antara yang bergerak secara legal formal dan mengikuti alur kultur yang alamiah. Budaya Sunda yang pada dasarnya bersifat terbuka mengalami ujian sejarah. Di dalam kalangan internal kebudayaannya muncul kehendak untuk lebih mengeksistensikan dirinya. Namun, kesadaran baru yang tumbuh pada masyarakat Sunda kemudian ialah pemahaman bahwa kelompok-kelompok etnis hidup dan saling berinteraksi dalam ruang kemajemukan.
Pendahuluan
Jika meminjam istilah Indra Jaya Piliang, elit Sunda sekarang sedang memegang “bola api demokrasi”. “Bola api” diandaikan sebagai sejenis permainan yang sangat membahayakan pemainnya. Secara peristilahan “bola api demokrasi” didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi yang sedang berlangsung. Liputan Kompas (15,16,17/12/2005) dan Pikiran Rakyat (12/12/2005) menyebutkan beberapa tokoh Sunda yang tergabung dalam Paguyuban Pasundan (PP) memprotes kebijakan Presiden SBY mengganti dua menteri putra Sunda dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Yusuf Anwar dan Andung Nitimiharja. Kebijakan itu dinilai sebagai meminggirkan kiprah elit Sunda di pentas nasional. Selanjutnya muncul pro dan kontra terhadap reaksi pengurus PP. Apabila disimpulkan terdapat dua “arus utama” pandangan yang mencuat. Pertama, mereka yang tetap menganggap penting prinsip keterwakilan etnis dalam perpolitikan nasional. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa mengedepankan semangat primordialisme hanya akan kontraproduktif bagi pembangunan bangsa.
Sejarawan Nina H. Lubis menyebut respon pengurus PP sebagai fenomena baru dalam tradisi elit Sunda yang berani menyatakan sikap secara terbuka. Pada dasarnya, budaya politik orang Sunda itu siger tengah (mencari posisi yang aman). Antropolog Budi Rajab menyebutnya sebagai ketidakmampuan elit Sunda mengadaptasi visi dan misi perubahan. Budayawan Sunda, Saini K.M. mengatakan kapabilitas personal tidak ada hubungannya dengan etnisitas. Oleh karena itu, orang Sunda harus lebih terbuka sehingga tidak emosional.
Diskursus tentang eksistensi Ki Sunda agaknya sudah menjadi klasik, namun tetap menarik diperbincangkan. Di dalamnya terdapat kecemasan-kecemasan dan harapan sekaligus. Perdebatan yang tidak pernah lebih maju dari kurun waktu sebelumnya membuktikan minimnya momentum untuk mengekspresikan diri. Dialognya hanya melingkupi orang-orang yang itu-itu saja dengan topik yang terbatas.
Menurut hemat penulis, pernyataan di atas tidak cukup membantu mengangkat peran politik orang Sunda di pentas nasional. Pernyataan tersebut lebih merupakan otokritik terhadap kondisi-kondisi internal. Apalagi ketika profesionalitas menjadi ikon zamannya, “protes” seperti itu cenderung dimaknai sebagai resistensi terhadap sistem yang berlaku. Padahal dalam beberapa budaya politik yang pernah dijalankan, meski dalam posisi yang menguntungkan, etnis Sunda tidak mengambil peran yang terlalu dominan. Tulisan di bawah ini mencoba mendeskripsikan beberapa persoalan internal, demokratisasi budaya, dan aktualisasi politik ki Sunda.
Krisis-krisis Internal
Pada dasarnya sejak konsep negara-bangsa ditegakkan sudah ada kesepakatan untuk menjadikan Indonesia sebagai “rumah baru” menggantikan rumah-rumah lokal yang sudah ada sebelumnya. Sutatdji Calzoum Bachri (2001) menyebut posisi pemimpin bangsa waktu itu sebagai Malin Kundang yang “durhaka” dengan meninggalkan”ibu kandung lokal” beralih ke “ibu nasional”. Hanya saja, eksistensi kelompok etnik kerap mengalami dinamika yang cukup drastis sebagai akibat intervensi negara. Formasi sosial politik yang mengepung eksistensi kelompok etnik sangat “cair”, karena dinamika sejarah yang sering berubah.
Mewacanakan soal representasi etnik dalam politik nasional hari ini lebih merupakan peneguhan sikap yang berangkat dari krisis-krisis internal dalam alam pikiran kelompok etnik. Sebagai contoh, dahulu etnik Minangkabau pernah mengalami krisis internal yang nyaris menggoncangkan seluruh sendi kehidupan secara keseluruhan akibat penumpasan PRRI (Pemerintah Revolusional Republik Indonesia). Ketika itu muncul stigma “Orang Minang kalah perang”. Terjadi krisis psikologis yang berakibat adanya perasaan inferioritas. Kelompok etnik yang pernah menyumbangkan putra terbaiknya dalam pencarian identitas bangsa dan perjuangan kemerdekaan, menjadi etnik yang dikalahkan. Gubernur Harun Sumatera Barat Harun Zain mengerek “Strategi Harga Diri” dalam rangka memulihkan martabat orang Minang. Dalam perjalanan sejarahnya, usaha mempertanyakan eksistensi etnik Minang dalam pergaulan antar sukubangsa terus berlangsung sampai hari ini. Suatu ketika Gus Dur melempar “bola Panas” dengan menyebut pemikiran orang Minang mandek. Reaksi yang positif dan negatif pun bermunculan.
Agaknya proses yang sama dialami orang Sunda dengan irama dan aksentuasi yang berbeda sesuai dengan tipikal Sunda yang lembut. Orang-orang Sunda yang pernah mempunyai tokoh nasional sekaliber Iwa Kusuma Sumantri, Djuanda Kartawidajaja, Otto Iskandardinata, Mochtar Kusumaatmaja, dan lain-lain agaknya risau dengan kenyataan politik yang tidak menguntungkan. Komposisi anggota DPRD Tk. I Jawab Barat, seperti yang disebut Setia Permana (2004), didominasi oleh orang non Sunda sungguh mengkhawatirkan sebagian elit Sunda. Demikian pula, pada jajaran birokrasi di pusat dan daerah terjadi kecenderungan yang sama. Pelan-pelan mereka tidak lagi menjadi tuan di ranahnya sendiri. Maka, jika sebagian elit Sunda memunculkan isu primodial dalam proses politik dapat dibaca sebagai upaya mencari keseimbangan dalam konstruksi bangunan kehidupan antar kelompok etnik dalam wadah kebangsaan. Bandung yang mewakili daerah Sunda seolah-olah terjepit dalam poros Jakarta-Yogyakarta. Terdapat kegamangan dalam mereposisikan peran sosiologis pada masyarakat yang terus berubah. Sunda seolah-olah sudah lebur dalam konsepsi nasionalitas kultur yang memusat sentripetal ke Jakarta.
Etnisitas sejatinya bersifat askriptif, tidak dapat dihilangkan, namun bisa tidak dipakai. Soal etnis tergantung bagaimana negara mengelolanya. Dahulu masa Orde Baru soal etnis (SARA) menjadi hantu yang menakutkan. Berbicara SARA berarti mengancam kestabilan negara. Orang menjadi takut untuk menegaskan identitas sukubangsanya. Kebudayaan berbagai sukubangsa dikumpulkan dalam etalase kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Maka, dibangunlah Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) yang berdiri dengan megahnya sebagai simbol ketundukan etnik terhadap negara. Kelompok etnik diredupkan peranannya dalam ruang-ruang sosial politik. Meski, misalnya pada masa itu sulit untuk tidak mengatakan Jawa sebagai “arus besar” dalam budaya politik nasional.
Masyarakat Sunda dikenal suka makan lalab-lalaban (sayur-sayuran). Konsumsi makan yang sebenarnya menyehatkan itu ditengarai mengembangkan masyarakat dengan karakter budaya yang lembut dan kurang kompetitif. Pendapat itu mungkin mengadopsi mentah-mentah pemikiran Aristoteles yang mengatakan bangsa-bangsa yang maju berasal dari masyarakat yang menghadapi tantangan alam yang berat.
Tantangan terbesar terletak pada kemampuan komunitasnya dalam mengadaptasi perubahan-perubahan. Dalam konteks ini, masyarakat Sunda harus mampu mentransformasikan kebudayaannya. Dahulu selalu ada ungkapan, “Jika kelompok mayoritas mapan, maka minoritas aman”. Sekarang, ungkapan itu agaknya sudah terpinggirkan secara wacana. Meski, dalam kenyataannya, terutama menyangkut hal yang strategis, dominasi tetap terasa. Ada semacam sentimen emosional menjadi tuan di tanahnya sendiri. Istilah populernya “Putra Asli Daerah”. Salah satu diktum dari teori fungsional struktural menurut van den Berghe dalam Lauer (1993) adalah integrasi sempurna tak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi.
Bandung sebagai pusat kekuasaan politik orang Sunda sekarang adalah kota metropolitan tempat berseminya ide-ide baru fashion, “kawah candradimuka” grup Band terkenal, dan budaya pop lainnya. Apa yang sedang trend di Bandung dengan segera diikuti daerah-daerah lain di Indonesia. Ada semacam gengsi sosial ketika mengikatkan diri kita dengan Bandung. Saya yang pernah bekerja di Padang selama lima tahun selalu berkata dari Bandung, meski sebenarnya orang Cikampek. Rekan-rekan yang orang Padang dengan bangga menyebutkan bahwa saya kawannya dari Bandung.
Bandung secara kultural sulit mengklaim dirinya sebagai pusat kebudayaan Sunda, seperti halnya Yogyakarta bagi kebudayaan Jawa. Secara kultural yang ada hanya konsep wilayah Priangan, yang meliputi Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, dan Sukabumi. Ada konsep Priangan (pusat) dan Pantai Utara/Selatan (Pesisir). Otoritas kultural amat terbatas ada pada wilayah berkesenian. Dengan ketiadaan primus inter pares itu, masing-masing daerah di Jawa Barat menegaskan identitasnya sendiri: wargi Karawang, wargi Sumedang, dan seterusnya.
Tumbuhnya gengsi sosial selalu menimbulkan kejenuhan ketika tidak diiringi dengan usaha meningkatkan kualitas. Masyarakat yang berasal dari berbagai daerah mengadu nasib ke Bandung. Sebagian dari mereka termasuk kelas menengah yang terdidik dan terampil. Dalam waktu yang tidak lama mereka mengambil peran penting menggeser orang-orang Sunda. Dalam jangka panjang sangat mungkin timbul resistensi sosial yang tercipta melalui radikalisasi massa dan ekspresi weapon of the weakness-nya James C. Scott (senjatanya orang-orang kalah). Radikalisasi dapat muncul mungkin melalui simbol-simbol keagamaan, kultur, bahkan kemiskinan. Radikalisasi tidak harus kekerasan fisik, dapat juga agresifitas dan sikap yang ofresif. Ketersingkiran sosial –meminjam istilah Scott- akan menciptakan sikap ekstrim yang lain: malas, tidak disiplin, dan maunya sendiri. Pokoknya sikap yang merusak keberaturan.
Tantangan cukup kuat memang terletak pada prestise di bidang pendidikan. Perguruan tinggi yang ada di Bandung dianggap kurang mampu menciptakan mazhab keilmuan yang menjadi kiblat bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Sementara tradisi intelektualnya tertahan dalam sekat-sekat materialisme dan hedonisme.
Dalam sistem internal orang Sunda terjadi pergeseran cara pandang. Sebuah penelitian yang dilakukan Yus Rusyana dan kawan-kawan (1988/1989) menyiratkan gambaran tersebut. Dahulu orang Sunda menganut bengkung ngariung bongkok ngaronyok (hidup bersama agar tidak jauh dari keluarga), sekarang mereka berusaha agar selalu sejahtera bersama keluarga. Dahulu orang Sunda harus bersabar walau sikap orang lain tidak wajar, sekarang mereka akan berterima sepanjang sikap orang lain wajar. Dahulu orang Sunda menganut sineger tengah, yaitu hidup layak tidak bermewah-mewahan juga tidak berkekurangan, sekarang mereka harus meraih apa yang bisa didapat. Jika tidak dapat, cukup dengan apa yang terjangkau.
Orang Sunda sebetulnya memiliki pengalaman kehidupan multietnik yang berjalan dengan damai. Migrasi orang-orang non etnik Sunda relatif berlangsung mulus karena penerimaan yang terbuka dari masyarakat setempat. Sebagian besar orang-orang perantau itu datang ke pusat-pusat kota sebagai jantung pemerintahan, ekonomi, dan menggeliatnya industrialisasi. Jika terjadi pergesekan antara warga setempat dengan pendatang jumlahnya tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, hal tersebut tidak merepresentasikan adanya konflik antar warga.
Dohrenwend dan Smith dalam (Lauer, 1993: 406) mengemukakan empat kemungkinan arah perubahan yang dapat dihasilkan dari kontak dua kebudayaan :
1. Pengasingan, menyangkut pembuangan cara-cara tradisional oleh anggota pendukung satu kebudayaan tanpa menerima cara-cara kebudayaan lain;
2. Reorientasi, menyangkut perubahan ke arah penerimaan strujktur normatif kebudayaan lain;
3. Penguatan kembali (reaffirmation) kebudayaan tradisional diperkokoh kembali;
4. Penataan kembali, kemunculan bentuk-bentuk baru seperti yang ditemukan dalam gerakan utopia.
Orang Sunda meminjam penelitian Ajip Rosyidi (1984) terhadap karya Sastra Sunda adalah orang-orang percaya diri, terbuka terhadap kritik, taat terhadap pemerintah, pembawaan sungguh-sungguh, dan jujur. Sebagian peneliti menyebut bahwa orang Sunda itu optimistis, berwawasan terbuka, namun perasa. Kiranya karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk mengangkat derajat kemanusiaan dan kesejahteraannya.
Agenda Kultural dan Politik
Ada beberapa agenda yang penting yang perlu dilakukan memperkuat tumbuhnya kepemimpinan Sunda dalam berbagai bidang.
Pertama, pelestarian nilai-nilai kepeloporan yang terkandung dalam tradisi Sunda hendaknya tidak dilakukan secara defensif. Harus ada proses kreatif yang terus ditransformasikan ke dalam ruang-ruang budaya. Selama ini melestarikan seolah-olah berarti tidak menerima unsur-unsur baru yang dapat memperkaya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal.
Kedua, pendidikan kesukubangsaan hendaknya diarahkan pada upaya mencari nilai-nilai positif dalam tradisi dengan menghindari sikap yang memupuk etnosentrisme. Warisan sejarah dan budaya dalam perjalanan bangsa menunjukkan adanya jaringan kolektif antar daerah dan etnik di Indonesia.
Ketiga, secara lebih luas masa depan sebuah entitas kultural ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Tantangan di masa depan hanya dapat dimenangkan oleh pemilik dari budaya unggul. Meski etnisitas tidak berkorelasi dengan keunggulan, namun stereotip etnis yang positif harus dikembangkan.
Keempat, era otonomi daerah hendaknya dimaknai sebagai proses meneguhkan identitas etnik dan menyesuaikannya dalam situasi yang terus berubah. Etnisitas yang sifatnya askriptif itu harus mampu mendorong tergalinya potensi-potensi lokal.
Kelima, perlu ada dukungan yang kuat dari kolektif orang Sunda yang dapat menopang anggotanya mencapai prestasi yang mengangkat pamor kesundaan. Dukungan tentu harus diberikan dengan memperhitungkan kemampuan seseorang.
Penutup
“Demokrasi lokal” dapat menjadi alternatif bagi demokrasi nasional yang sedang mengalami disfungsi sosial akibat hegemoni Orde Baru. Orang Sunda memiliki banyak kesempatan untuk merekonstruksikan nilai-nilai kelokalannya dalam hidup bersama kelompok etnik-etnik lain. Inilah mementum terbaik untuk meneguhkan kembali identitas etnik di tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks.
Perspektif kepemimpinan Sunda hendaknya tidak selalu dilihat sebagai kembali ke masa lalu. Banyak kelompok etnik yang berupaya membangkitkan batang terendam kebudayaan lokalnya dengan mengadaptasinya dalam perspektif modern. Orang Sunda meski tidak dapat lagi menetapkan garis teritorial-genealogisnya secara jelas, memiliki kesanggupan menegaskan identitas etnik tanpa terjebak dengan inward looking (pandangan yang terlalu ke dalam).****
Daftar Sumber
Harsojo. 1983. “Kebudayaan Sunda”, dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Lauer, Robert H. 1993. Perspektif tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
Permana, Setia. “Konsep Kepemimpinan Sunda di Persimpangan Jalan, Makalah dalam Diskusi Kepemimpinan Sunda dalam Perspektif Sejarah, 17-18 September 2003, Museum Mandala Wangsit Bandung.
Rusyana, Yus dkk. 1988/1989. Pandangan Hidup Orang Sunda seperti Tercermin dalam Kehidupan Masyarakat Dewasa ini Tahap III. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Bagpro Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Depdikbud.
Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.